Keberadaan spesies asing invasif atau Invasive Alien Species (IAS) telah lama dikenal sebagai ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem alami, serta fungsi ekologis di berbagai belahan dunia. Namun, dalam konteks tertentu, kehadiran spesies ini justru menciptakan dinamika yang unik, terutama ketika dikaitkan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Studi kasus yang dilakukan oleh Endratno Budi Santosa dan Nindyasari di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Indonesia, memperlihatkan bahwa dua jenis spesies IAS, yakni adas (Foeniculum vulgare) dan kirinyuh atau slimmer weed (Chromolaena odorata), bukan semata menjadi beban ekologis, melainkan juga sumber daya yang bernilai bagi komunitas masyarakat Tengger di desa enclave.
Desa enclave yang dimaksud merupakan wilayah permukiman masyarakat adat Tengger yang secara geografis terletak di dalam batas administratif taman nasional. Keberadaan mereka dalam ruang konservasi menghadirkan tantangan pengelolaan kawasan yang kompleks, namun juga membuka kemungkinan munculnya praktik adaptif berbasis kearifan lokal. Dalam kerangka penelitian ini, dilakukan pendekatan literatur semi-struktural berdasarkan basis data ilmiah Scopus dan dianalisis secara deskriptif melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk pengelola taman nasional, perangkat pemerintahan desa dan kecamatan, organisasi non-pemerintah, serta kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pemanfaatan tumbuhan IAS.
Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian terdahulu terkait spesies adas dan kirinyuh, khususnya yang berfokus pada pemanfaatan di wilayah Indonesia, masih sangat terbatas. Padahal, kedua spesies tersebut memiliki keterkaitan mendalam dengan kehidupan masyarakat lokal, baik dalam konteks budaya maupun ekonomi. Adas, misalnya, digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional dan menjadi bagian penting dalam berbagai ritual keagamaan dan budaya masyarakat Tengger. Begitu juga dengan kirinyuh yang walaupun secara ekologis dianggap merusak dan mendominasi lahan, nyatanya telah dimanfaatkan sebagai bahan alternatif obat luar dan pengusir serangga oleh masyarakat setempat. Ketersediaan tumbuhan ini yang melimpah menjadikannya mudah diakses dan murah, serta secara tidak langsung mendukung sistem pengobatan lokal yang berbasis pada pengetahuan turun-temurun.
Kondisi ini menempatkan spesies IAS dalam suatu kerangka ambivalen, yakni sebagai ancaman ekologis sekaligus peluang sosio-ekonomi. Ambivalensi ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam pengambilan kebijakan konservasi berbasis masyarakat. Ketika sebuah spesies asing yang invasif tidak dapat sepenuhnya diberantas, pendekatan pengelolaan yang mengarah pada pemanfaatan berkelanjutan menjadi pilihan strategis. Dalam hal ini, pemahaman terhadap nilai budaya dan ekonomi dari spesies tersebut menjadi modal penting dalam perumusan strategi konservasi yang adaptif dan partisipatif.
Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model pengelolaan yang lebih integratif, yang tidak hanya berfokus pada aspek pemberantasan spesies invasif, melainkan juga mengakui dan memfasilitasi pemanfaatan berkelanjutan oleh komunitas lokal. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi seperti taman nasional, paradigma ini dikenal sebagai konservasi kolaboratif. Model ini mensyaratkan pengakuan terhadap hak dan praktik tradisional masyarakat lokal, serta membuka ruang dialog antara pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan lokal yang diwariskan secara lisan.
Kelebihan dari pendekatan integratif semacam ini terletak pada kemampuannya untuk meminimalkan konflik antara kebijakan konservasi dan kebutuhan masyarakat yang hidup bergantung pada sumber daya lokal. Dalam kasus adas dan kirinyuh di kawasan Tengger, pengelolaan yang didasarkan pada pemanfaatan tradisional dapat menghasilkan hasil ganda, yakni pengurangan dampak ekologis akibat dominasi spesies invasif, serta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian komunitas lokal. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman hayati sekaligus keragaman budaya tinggi, di mana praktik pemanfaatan tumbuhan lokal memiliki nilai ekonomi, spiritual, dan sosial yang tidak tergantikan.
Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah mengenai pengelolaan spesies asing invasif, tetapi juga membuka ruang wacana baru tentang bagaimana pendekatan sosial-ekologis dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks konservasi kawasan. Ke depannya, penting untuk mengembangkan kebijakan yang bersifat fleksibel dan kontekstual, termasuk skema insentif, pendidikan konservasi, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengendalian spesies IAS. Dengan demikian, studi yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini memberikan gambaran nyata bahwa kehadiran spesies asing invasif tidak selalu harus dilihat sebagai persoalan ekologis semata. Ketika dipahami secara menyeluruh dan diposisikan dalam sistem sosial-budaya masyarakat lokal, spesies invasif seperti adas dan kirinyuh dapat menjadi jembatan menuju pendekatan konservasi yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal.
Sumber:
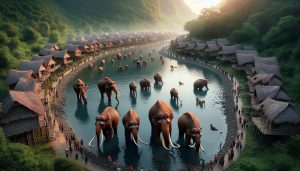
Leave a Reply